Review Acehnologi (II:18 Antropologi Aceh)
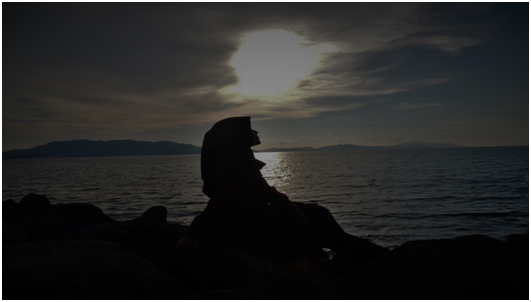
Pada saat saya membaca bab ini saya langsung di suguhkan dengan bacaan “local scholars” tidak memiliki kualitas akademik yang baik di bandingkan dengan “International scholars”. Dan di sini saya bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya sehingga ini menjadi guyonan dan komentar di dalam berbagai forum dan pertemuan formal ataupun informal. Ternyata jawabannya adalah karena ketidak mampuan sarjana lokal dalam menghasilkan karya-karya yang dapat di rujuk oleh sarjana Internasional, di samping itu “sarjana lokal” sering hanya mengejar KUM untuk naik pangkat. Kondisi ini tentu saja bukanlah sesuatu hal yang harus di terima sebagai takdir akademik.
Ketika sarjana internasional melakukan riset atau penelitian di Aceh tentu saja mereka akan menghubungi sarjana lokal, sang sarjana lokal akan menceritakan seperti yang diinginkan oleh sang tamu. Di dalam dialog sang tamu akan banyak diam dan mendengarkan terhadap apa saja yang di beritahu sarjana lokal dengan tatapan ingin memberikan kesempatan terus menerus supaya sarjana lokal terus membagi informasi terhadap sang tamu. Setelah itu, mereka akan melakukan pertemuan dengan beberapa informan salah satu list yang paling di buru oleh sarjana Internasional atau tamu ini adalah orang yang berpengaruh di Aceh, orang yang paling sering menyampaikan opini publik begitulah mereka melakukan riset di Aceh.
Namun sayang amat di sayang kan terkadang sarjana Internasional menyimpan sesuatu yang tidak dapat di percaya begitu saja, di mana mereka tidak pernah memberitahukan jati diri mereka yang sebenarnya, kecuali sebagai dosen atau peneliti dari kampus tertentu. Dan terkadang beberapa peneliti luar yang komplain karena data mereka selalau tidak cukup ketika berada di Aceh, hal ini di karenakan data yang bersifat “membahayakan” citra Aceh di mata Internasional tidak di berikan kepadanya. Persoalan-persoalan yang kerap di ungkit dari peneliti luar adalah “apa yang salah dengan Aceh” bukan menjelaskan secara komprehensif. Bebarapa peneliti luar bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi orang Aceh di daerah perkampungan. Imajinasi yang terbayang oleh mereka adalah orang Aceh seperti pada masa rehab rekon pasca-Tsunami, padahal di beberapa wilayah gampong yang berdekatan dengan bukit dan gunung orang Aceh masih dengan sistem yang masih serba Aceh. Karena itu bebebrapa peneliti luar merasa kewalahan untuk mencari data di perkampungan kekesalan ini terkadang di luapkan di dalam tulisan mereka belum lagi wartawan yang terkadang membelokkan hasil wawancara mereka dengan informan Aceh. Memang tidak semua peneliti luar begitu dan disini kita tentu bukan untuk menghakimi tentang dunia riset yang di lakoni peneliti luar di Aceh.
Pasca-Tsunami kedatangan warga asing ke Aceh meningkat pesat tetapi sejauh ini konsentrasi warga asing lebih banyak di lihat di ibu kota provinsi, dan warga asing bebas berkeliaran di Aceh ada juga yang mengangkut hasil bumi keluar negeri sepengetahuan pemerintah istilah investasi adalah kata keramat yang sering di munculkan di atas selimut operasi intelijen. Bangsa lain mengeruk hasil bumi Aceh sementara uang mereka kita gunakan untuk membeli barang-barang impor, harus diakui bahwa semua prilaku ini bagian dari operasi intelijen. Pada buku acehnologi volume dua halaman 554 dikatakan salah satu modus dari beberapa modus adalah di negara-negara asia timur setiap negara baik sipil maupun militer telah mengenyam pendidikan wajib militer, istilah wajib militer merupakan bagian terpenting di dalam membentuk sel-sel intelijen sesungguhnya telah menunjukkan kualifikasi tingkat kebertahanan mereka, dengan alam dan orang Aceh sebagai seorang agen.
Sebagai contoh ada warga asing yang sudah menguasai lahan pinggir pantai simeulue sebagai lahan bisnis mereka, mereka membeli tanah lokal atas nama warga Indonesia. Minimnya kontrol terhadap kedatangan warga asing menyebabkan lemahnya daya tawar pemerintah terhadap tindak tanduk warga asing di pulau tersebut pada gilirannya menyebabkan ada kegiatan-kegiatan yang tidak dapat di masuki otoritas setepat mengenai warga asing di kawasan tersebut. Kajian Antropologi dengan kedatangan orang asing di temapat-tempat tertentu merupakan dua mata koin yang tidak dapat di pisahkan. Terlepas dari cara dan upaya orang asing menetap di Aceh, namun strategi mereka hampir mirip dengan pengalaman para antropolog ulung pada zaman perang dunia satu I dua II. Mereka dikirim oleh negara mereka untuk “membuka” pemahaman tentang wilayah yang menjadi target, kemudian mereka “menyisir” setiap aspek kebudayaan sebagai seorang etnografer.
Kajian Antropologi Aceh adalah berusaha untuk membangun kembali pemahaman kebudayaan Aceh dan juga semangat orang Aceh dalam “carrying their own culture to other places and culture” pola ini pada gilirannya akan membantu orang Aceh di dalam memahami kebudayaan mereka sendiri dan mengetahui cara-cara untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga terus memupuk pengetahuan mereka di dalam menghadapi era kontemporer. Kajian Antropologi di Aceh tampaknya lebih banyak berupaya untuk menjelaskan kebudayaan masyarakat di pegunungan dan pesisir. Persoalan yang agak krusial adalah bagaimana mendifinisikan Aceh dalam konteks identitas khususnya, ketika hendak di bangun pola-pola studi budaya yang ada di Aceh. Hal ini di sebabkan adanya beberapa sub-identitas yang ada di Aceh sendiri.
Di Aceh, secara sosio-histori, cenderung di gunakan bahasa melayu, sebagai bahasa pengantar di dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua masyarakat tersebut menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar. Kekayaan khazanah budaya juga ikut memicu adanya sub-sub varian etnik yang ada di provensi ini. Kekayaan dari sisi bahasa dan budaya, tampaknya dapat di jadikan modal dasar untuk membangun ilmu antropologi Aceh. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa studi antropologi Aceh adalah melakukan pengkajian terhadap budaya-budaya yang ada di Aceh. Pada halaman 574 dalam buku Acehnologi volume dua sub kajian antropologi terdapat empat bidang, pertama, kajian antropologi kultural memiliki objek kajian tentang asal usul, sejarah,dan perkembangan kebudayaan masyarakat. Kedua, arkaeologi berupaya memahami benda-benda yang merupakan hasil dari kebudayaan masyarakat terdahulu. Ketiga, biologi-Antropologi berupaya untuk melihat aspek-aspek bologis dalam diri manusia. Keempat, antropologi linguistik berupaya menelaah bahasa-bahasa yang ada di dalam suatu masyarakat, terutama yang terkait dengan struktur dan aturan-aturan di dalam bahasa.
Pada halaman 582-587 di katakan untuk memudahkan wilayah kerja Antropologi Aceh di bagikan wilayah kebudayaan Aceh. Wilayah pertama adalah kebudayaan masyarakat kota Banda Aceh yang merupakan wilayah yang urban di provinsi Aceh, wilayah kedua adalah wilayah perbukitan-persawahan-penggunungan yang ada di Aceh Besar mulai dari saree perbatasan dengan Aceh Pidie, hingga ke lhong, pebatasan dengan kabupaten Aceh Jaya, wilayah ketiga adalah wilayah kebudayaan pidie hingga ke pegunungan yang berbatasan langsung dengan Aceh Barat dan Bireun kawasan ini menjadi begitu unik, karena terdapat diaspora masyarakat pidie, tidak hanya di seluruh Aceh tetapi juga di luar Aceh, wilayah kelima kawasan dari sungai kreung mane hingga ke sungai jambo aye, wilayah keenam kawasan dari perbatasan Aceh timur dengan Aceh utara hingga memasuki wilayah kota langsa, wilayah ketujuh kawasan langsa hingga perbatasan dengan sumatra utara, wilayah kedelapan kawasan Aceh Tenggara dan sekitarnya yang juga memiliki hubungan yang amat kuat dengan provinsi tetangga, kawasan kesembilan kebudayaan di Aceh adalah singkil dan sekitarnya, kesepuluh yang berada di wilayah subulussalam hingga ke Aceh selatan, wilayah kesebelas Aceh selatan hingga Aceh barat daya wilayah ini terdiri dari wilayah pesisir dan perbukitan yang telah banyak mengundang sejumlah para peneliti, wilayah keduabelas nagan raya masih benar-benar mempertahanka kebudayaan Aceh, dan yang ketigabelas dan merupakan wilayah terakhir adalah meulaboh hingga ke lamno.