HALTE DAN HUJAN
Halte dan Hujan
“Jam setengah dua.” Aku ke luar dari kampus sambil berlari-lari kecil. Gerimis memaksaku mempercepat langkah. Menyeberang jalan, menutupi kepalaku dengan tas parasut berwarna sepia, aku melengak-lengok mencari tempat yang dapat menghindarkanku dari tusukan rintik air. Sejak mata kuliah terakhir, aku sudah cemas melihat warna langit yang redup, awan menggumpal disertai kilat berkelebat-kelebat. Tak ada matahari. Cuaca dan kelam langit membuatku teringat wajah murka Zeus dalam mitologi Yunani kuno yang pernah aku baca.
Ketika aku sampai di halte, gerimis mempercepat frekuensinya. Deru suaranya seperti dzikir sejuta malaikat yang tak hikmat. Hujan lebat, disertai gelegar petir, deru bus, dan koar bajaj yang kejar-mengejar mulai mengaburkan pendengaran dan pandanganku. Kini yang bisa aku lakukan hanya duduk di bangku halte, mengipat-ngipatkan sisa air yang menempel di tubuh dan bajuku, sambil sesekali mengumpat hari dan cuaca yang buruk. Namun aku merasa sedikit lega karena hujan tak sampai membuatku kuyup — meski kini kepalaku mulai sedikit pening. Di sekitarku, di lantai halte yang berwarna tanah campur pasir, aku lihat seekor kecoa terbalik, dua botol aqua yang telah terinjak, serpihan koran, daun-daun kering yang basah terkena air hujan, serta empat bungkus rokok yang sudah diremas: dji sam soe, djarum super, marlboro, dan gudang garam filter. Aku melihat besi-besi halte yang berkarat, bangku duduk yang hilang setengah, serta cat besi yang terkelupas dan warnanya bersaing dengan warna coretan pilok.
Di pojok sebelah sana, sebelah kiri dari tempat aku duduk, nampak berdampingan dua sosok manusia. Rambut mereka sama-sama panjang, sama-sama hitam, sama-sama mengilat basah terkena air hujan. Hanya dari pakaian mereka aku tahu bahwa dua sosok itu adalah laki-laki dan perempuan. Mereka berbisik-bisik satu kepada lainnya, kemudian diam, lalu kembali berbisik, diam, kemudian bersintuhan — tangan yang laki-laki berada di atas tangan yang perempuan. Untuk beberapa saat keduanya hanya memandang ke depan, ke arah hujan. Keduanya terlihat murung, dengan tatapan jauh menerawang seakan menyibak sekat-sekat tirai yang terbentuk dari rintik hujan. Kedua mata yang perempuan nampak sembab kemerahan, sementara wajah yang laki-laki nampak muram seperti menanggungkan beban. Terpikir olehku bahwa mereka mungkin adalah teman karib, atau kakak beradik, atau sepasang kekasih, atau suami istri, atau mungkin juga mereka adalah dua orang asing yang baru saja bertemu di halte ini ketika — seperti diriku — sama-sama ingin menyelamatkan diri dari teror hujan. Kembali mereka berbisik-bisik, kemudian diam, kemudian bersintuhan dan hanya bersintuhan — kini tangan yang perempuan berada di atas tangan yang laki-laki. Yang perempuan kini menunduk, memandangi saputangan putih yang terlipat rapi di pangkuannya, sementara yang laki-laki terus saja memandang jauh ke depan. Aku tercenung sejenak melihat adegan ini, dan entah mengapa ingatanku segera terbawa pada sebuah puisi dari seorang penyair terkenal yang berjudul Di Kebun Jepun. Sambil terus menatap ke arah dua sosok itu, perlahan aku mencoba mengingat — dengan mengubah beberapa kata atau larik — baris-baris puisi yang aku kira kini lebih pas diberi judul Di Halte Bus:
Di halte itu sepasang orang asing
berbisik tentang jalan dan hujan.
“Alangkah sedihnya,” kata yang perempuan,
“kita tak tahu nama jalan dan rintik hujan.”
“Aku pun tak tahu siapa namamu,” jawab yang laki-
laki,
“Kau tak tahu siapa namaku, tapi kita tak sedih.”
“Tapi aku tahu siapa namamu, kau tahu siapa namaku.”
“Hanya sebagian.”
“Hanya sebagian. Tapi kau telah membedakanku dari
yang
lain, sementara kita tak bisa membedakan rintik-rintik
ini
dari yang lain, untuk suatu saat lain.”
“Tapi kau bukan rintik hujan. Aku tak bisa melupakanmu.”
Memang manis kedengarannya. Mungkin romantis.
Mungkin lucu. Dan terlambat.
Mereka bukan anak-anak muda dari sebuah novel.
Mereka hanya bayang-bayang, menghitam oleh usia,
mencari nyali
dalam keramat badai, dan akan hilang sendiri-sen
diri
bila tiba gelap.
Dan gelap juga akan tiba di halte itu.
Maka pada halte tanpa nama, di teduh halte
tanpa nama,
mereka duduk. Mereka ingin saling membujuk,
mungkin
memeluk. Tapi kemudian, cuma bersintuhan.
Hanya bersintuhan! Mereka takut. Kenangan bisa
hanya beban, cinta tak ada jalan keluar, matahari
hanya sebentar.
“Matahari hanya sebentar. Besok kita masing-masing
pergi.”
Dan perempuan itu, 25 tahun, teringat kekasihnya.
Dan laki-laki itu, 25 tahun, teringat teman-temannya.
“Lalu?”
“Jangan tanyakan itu.”
“Perasaan kita ternyata sialan dan sia-sia,
tak ada gunanya.”
Sungguh benar! Laki-laki itu ingin bersiul, mengelakkan putus asa. Laki-laki itu ingin berkata:
“Hujan juga sialan dan sia-sia, tak ada gunanya.”
“Juga nama jalan,” perempuan itu menyambung.
Dan mereka saling tersenyum, sakit, senyum, pahit,
sementara bus-bus kota yang keras tak mengacuh
kan
rintik hujan (mungkin sebuah ilham) jatuh terpercik mengalir pada
jalan.
“Lalu, apa yang berguna?”
“Semut-semut,” sembur yang laki-laki. Mereka ter-
senyum,
memandangi sebaris semut mendaki dinding halte, menghin-
dari basah.
“Atau,” sambungnya, “yang berguna adalah gangsa.”
“Tapi di halte ini tak ada gangsa.”
Laki-laki itu mengangguk. Tak ada, tapi itulah yang
mereka cari: seekor merpati yang putih dan seekor lagi
merpati yang putih, berdiri di kejauhan pada kabel di kanan halte
itu,
membersihkan bulu, membasuh diri pada hujan.
Kita butuh fantasi, pasangan itu ingin berbisik.
Tapi mereka tak berbisik. Hanya bersintuhan, sekali
lagi.
Aku tersenyum dan merasa sedikit terhibur. Dua sosok manusia itu paling tidak telah membuatku sedikit mengabaikan hujan yang aku kira sudah berlangsung setengah jam. Sambil memperhatikan mereka, terlintas pertanyaan di benakku apakah mereka juga pernah membaca sajak itu, dan kini secara kebetulan mengalami kejadian yang kurang lebih mirip dengan yang digambarkan dalam sajak itu? Aku tersenyum dan segera mengabaikan pertanyaan itu. Aku terus memperhatikan mereka sambil berharap bahwa hal itu dapat terus membuatku mengabaikan hujan. Namun karena kedua sosok manusia itu terus saja diam, hanya bersintuhan, hanya memandang kosong ke depan, lama-kelamaan aku merasa bosan. Aku mengalihkan pandangan. Namun kembali yang terlihat dan terdengar hanya hujan dan hujan yang gaduh. Sesekali petir, deru bus, dan koar bajaj menyela sebagai selingan. Setengah jam lebih hujan turun dan kini air mulai menggenang di cekungan-cekungan jalan.
“Jam dua lebih limabelas menit.” Aku mengeluarkan rokok, menyalakannya dan berusaha menghibur diriku dengan kepulan-kepulan asapnya. Sekilas aku kembali menoleh ke kiri, dan, seperti manekin, kedua sosok manusia itu tetap saja diam, bersintuhan, dan terus menerawang kosong ke depan. Aku mengalihkan pandangan sambil menghisap rokokku dalam-dalam. Kehangatan yang merambat dari tembakau yang terbakar, kemudian menjadi asap, masuk ke dalam mulutku, menerobos tenggorokan dan kemudian menjalar sedikit demi sedikit ke seluruh tubuhku perlahan mulai membuatku dapat sepenuhnya mengabaikan dua sosok manusia di sebelah kiriku. Pandanganku kini sepenuhnya terarah lurus ke depan. Sambil memain-mainkan batang rokok yang ada di tangan kananku dan menatap jingkat-jingkat hujan, aku berusaha sedikit demi sedikit menyibak sekat-sekat pandang yang terbentuk oleh deras rintik hujan dan kabut tipis mengilat yang mulai turun.
Di seberang jalan, aku melihat sebuah kios rokok yang tertutup. Sebuah pohon waru besar berdiri di belakang kios itu dan nampak hampir roboh. Di samping kios itu, berdiri sebuah halte yang warna dan bentuknya tidak jauh berbeda dengan halte tempatku berteduh. Hanya saja penampilannya agak sedikit ramping. Sejenak terlintas sebuah pikiran dalam benakku bahwa mungkin kedua halte ini dulu adalah sepasang kekasih, atau sahabat karib, atau kakak beradik, atau suami istri yang akhirnya berpisah gara-gara begitu banyak dan silih berganti orang asing yang memasukinya. Aku tersenyum dan segera mengabaikan pikiran itu. Di dalam halte itu terlihat seorang lelaki berkacamata, dengan kemeja berwarna putih, dasi hitam — atau biru tua — bergaris-garis putih. Ia memakai celana berwarna abu-abu dan sepatu berwarna hitam yang mengilat terkena air hujan.
Meskipun terhalang oleh hujan, aku dapat melihat bahwa orang itu cemas. Kepalanya terus-menerus bergerak ke kanan, ke kiri, atas, bawah, depan, belakang, dan sesekali ia memandangi jam tangan hitam yang melilit tangan kirinya.
Tak berapa lama kemudian, pemandangan ini pun membuatku bosan. Aku mengalihkan pandangan dan berusaha mencari-cari sesuatu yang lain yang dapat membuatku mengabaikan hujan. Aku kembali menoleh ke kiri, namun sama: dua sosok manusia itu masih saja diam, bersintuhan, dan terus menerawang kosong ke depan. Aku membuang rokokku yang baranya sudah menyentuh gabus. Mengambil satu lagi, aku segera menyalakan dan menghisapnya dalam-dalam. Kini yang dapat aku lakukan hanya memain-mainkan batang rokok sambil mengamati apa saja yang melintas di jalan: mobil, bus, mikrolet, sepeda motor, serta bajaj yang saling silang berkejaran.
Tanpa sepenuhnya aku ketahui dari mana datangnya, aku melihat sedikit demi sedikit jalanan di depanku terkikis, meriap sejengkal demi sejengkal, berubah menjadi pekarangan luas sebuah pedesaan dengan beberapa pohon pisang dan randu di sekitarnya. Tanahnya berwarna merah kecoklatan, hingga air hujan yang jatuh menyentuhnya juga ikut menjadi merah kecoklatan. Beberapa rumah yang bertiang kayu mahoni, berdinding anyaman bambu, dan beratap anyaman daun kelapa kering berdiri berderet menghadap ke pekarangan. Hujan lebat dan angin kencang menggoyang-goyang atap rumah-rumah itu. Berangsur-angsur sosok-sosok kecil dengan wajah kanak-kanak bermunculan. Dengan penuh keriangan, seperti merayakan hujan, mereka berlari-larian saling mengejar. Sesekali mereka sengaja menjatuhkan diri, masuk ke dalam genangan air hujan pada tanah cekung, berguling-guling, berdiri kembali dan kemudian kembali berlari-larian saling mengejar. Hujan turun semakin lebat. Ada empat bocah yang bermain dengan hujan di pekarangan itu: yang satu berambut lurus terbelah di tengah, berusia sekitar sepuluh tahun; yang satunya lagi, berambut ikal — seperti milikku — dengan kulit coklat berumur sekitar sebelas tahun; yang satunya lagi berambut keriting berkulit kuning langsat berusia sekitar sembilan tahun; dan yang satunya lagi berambut lurus, bermata sipit, berumur sekitar sepuluh tahun.
“Cihuyy…,” “ya…,” “haiyaa…,” “ciuuu…ssss,” mereka terus berlarian, mengabaikan hujan, saling mengejar dan berusaha menangkap satu sama lain. Lumpur, kelebat-kelebat kilat, dan bunyi petir yang sesekali menggelegar, tidak mengurangi keceriaan mereka dalam permainan dalam hujan. Sesekali mereka berkumpul, berangkulan, saling melepotkan lumpur ke wajah dan tubuh temannya, saling mendorong, dan kemudian kembali berlarian saling mengejar….
Suara isak yang semakin jelas terdengar dari sebelah kiriku membuat aku terhenyak. Lamunanku buyar. Rokok di tanganku jatuh dan langsung mati dirembesi air. Aku segera mengambl satu lagi dan langsung membakarnya. Sekilas aku melihat jarum jam di tanganku menunjukkan pukul dua lebih empatpuluh lima menit. Hujan masih sederas dan selebat sebelumnya — atau mungkin semakin bertambah lebat. Aku menoleh dan melihat laki-laki itu kini berdiri menghadap ke arah si perempuan. Kedua tangannya berusaha memegang bahu si perempuan, namun perempuan itu terus mengelakkannya sambil sesekali mendorongnya mundur.
“Nggak mungkin, Di, nggak mungkin......” ucap yang perempuan sambil mengibaskan kedua tangan laki-laki itu dari bahunya. Suaranya terpatah-patah menahan isak. “Kau tahu aku siapa. Sudahlah, kita berhubungan seperti ini saja....”
“Tapi kau tahu, La, aku sangat mencintaimu!” Laki-laki itu mendekatkan wajahnya sambil terus berusaha memegang bahu wanita itu.
“Tapi...., keluargamu?”
“Aku tak peduli!”
“Tapi aku pelacur, Di...!”
“Aku tak peduli, La! Aku tak peduli! Ayolah, kita tinggalkan saja kota ini!”
“Nggak mungkin, Di, aku nggak bisa...”
“La...! Aku......,”
Gelegar geledek meledak keras menggetarkan atap halte hingga aku dan kedua sosok manusia di sebelah kiriku itu tersentak. Rokok di tanganku kembali terjatuh. Kedua sosok di sebelah kiriku kini berpelukan. Wajah yang laki-laki terbenam di dada yang perempuan. Serentetan geledek kembali terdengar keras saling silang. Hujan masih selebat sebelumnya — atau mungkin semakin bertambah deras. Aku melihat jarum jam di tanganku menunjukkan pukul tiga lebih tiga menit. Dari trotoar di sebelah kiri halte, aku melihat seorang perempuan dengan paras kearab-araban masuk ke dalam halte dan langsung duduk di samping kedua orang yang masih berpelukan itu. Beberapa saat ia mengipat-ngipatkan air hujan yang hampir membuatnya kuyup. Aku tersentak, sedikit kaget. Ada sesuatu yang tiba-tiba saja masuk ke dalam kepalaku. Paras perempuan yang baru saja masuk berteduh itu segera menyadarkanku bahwa aku mempunyai janji dengan seorang gadis dalam waktu setengah jam lagi. Aku juga ingat bahwa pukul empat nanti di SCTV akan diputar serial telenovela Esmeralda kesukaanku. Aku memandang sekeliling, dan melihat hujan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Aku mulai gelisah dan semakin menjadi gelisah. Hujan masih sederas dan selebat sebelumnya.
Tepat ketika jarum jam di tanganku menunjukkan pukul tiga lebih tigabelas menit, aku melesat, berlari menerobos hujan ke sebelah Barat, menuju kosku yang berjarak kurang lebih satu setengah kilometer lagi.***
[P.S.: Cerpen ini juga terdapat dalam buku kumpulan cerpen saya yang berjudul "Matinya Seorang Atheis".
Book details:
Paperback
Published: June 2011
Publisher: Koekoesan
ISBN: 9789791442497
Language: Indonesian
Original title: Matinya Seorang Atheis
Literary Awards: short list Khatulistiwa Literary Award]
Link:
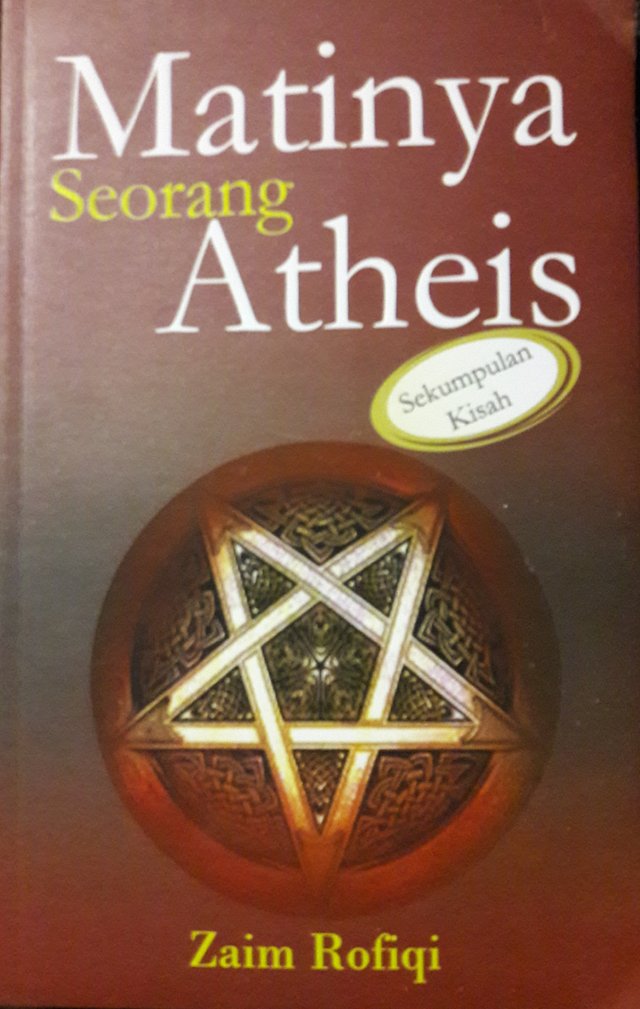

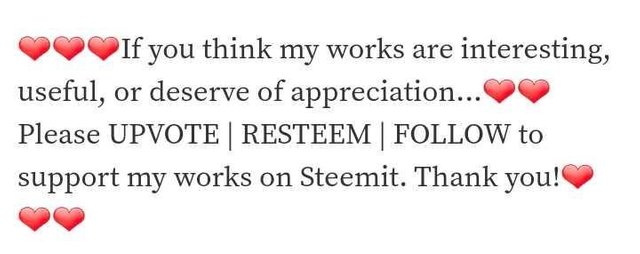
@zaimrofiqi upvoted this post via @poetsunit!!

Poetsunited - DISCORD - @poetsunited - witness upvote
Halo @zaimrofiqi, terima kasih telah menulis konten yang kreatif! Garuda telah menghampiri tulisanmu dan diberi penghargaan oleh @the-garuda. The Garuda adalah semua tentang konten kreatif di blockchain seperti yang kamu posting. Gunakan tag indonesia dan garudakita untuk memudahkan kami menemukan tulisanmu.Tetap menghadirkan konten kreatif ya, Steem On!
Terima kasih...
Wah, ada bbrp kata yg baru saya dengar dsini mas; bersintuhan? Mengipat-ngipatkan? Gangsa?
Apa mungkin saya kurang banyak baca ya 😅
Moga aja nambah wawasan, Sis @diyanti86...
Trims yaa...😀
Congratulations @zaimrofiqi: this post has been upvoted by @minnowhelpme!!
This is a free upvote bot, part of the project called @steemrepo , made for you by the witness @yanosh01.
Thanks for being here!!